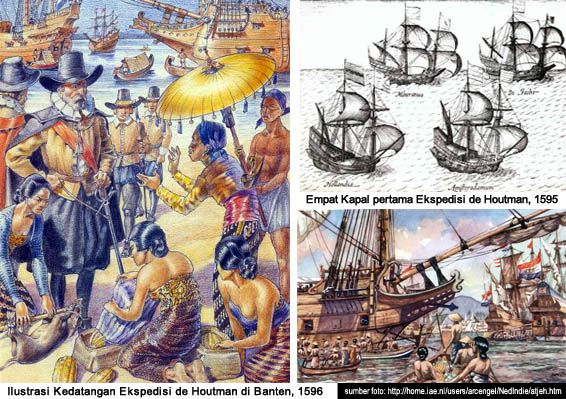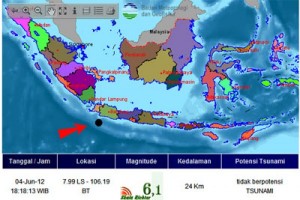Rabu, 26 September 2012 |
 Shutterstock
ShutterstockIlustrasi
Oleh Saldi Isra
Tanpa
harus menunggu perhitungan akhir Komisi Pemilihan Umum Daerah, hasil
pemilihan gubernur DKI Jakarta: pasangan calon Joko Widodo-Basuki
Tjahaja Purnama (Jokowi-Basuki) menang atas pasangan Fauzi Bowo-
Nachrowi Ramli (Foke-Nara).
Bahkan, tak perlu waktu lama pula,
Fauzi Bowo pun langsung memberikan ucapan selamat kepada Jokowi. Dalam
batas penalaran yang wajar, hasil pemilihan gubernur DKI Jakarta
seharusnya dimenangkan oleh pasangan Foke-Nara. Selain posisi Foke yang
petahana gubernur DKI Jakarta, pasangan Foke-Nara didukung pula oleh
koalisi Partai Demokrat, Golkar, Hanura, PAN, PKB, PBB, PMB, PKNU, PPP,
dan PKS. Berdasarkan hasil pemilu anggota DPRD DKI Jakarta 2009,
koalisi tambun (over-size) parpol pendukung Foke-Nara ini meraih lebih
dari 73 persen suara pemilih.
Sementara itu, masih dalam batas
penalaran yang wajar pula, harusnya duet Jokowi-Basuki tak masuk
putaran kedua, apalagi memenangi pemilihan. Selain bukan petahana di
DKI Jakarta, Jokowi-Basuki hanya didukung oleh PDI-P dan Gerindra
dengan dukungan suara kurang dari 16 persen pemilih. Jikalau hanya
melihat basis dukungan parpol, capaian Jokowi-Basuki dapat dinilai amat
fenomenal.
Dari berbagai perspektif, kemenangan Jokowi-Basuki
adalah bentuk kemenangan akal sehat dan sekaligus kehancuran
pragmatisme parpol pendukung Foke-Nara. Dikatakan begitu, gejala umum
yang berkembang beberapa waktu belakangan, parpol lebih mengandalkan
dukungan uang dan kekuasaan daripada figur yang punya pemahaman kuat
terhadap kebutuhan rakyat.
Merujuk bentangan fakta hasil
pemilihan gubernur DKI, yang perlu dapat apresiasi adalah logika
pemilih tak mau ditaklukkan oleh logika parpol. Bahkan, saat parpol
berjalan dengan logikanya sendiri, berapa pun banyak dan besarnya
koalisi dibangun, pemilih mampu membuktikan, daulat rakyat lebih
mangkus dibandingkan daulat parpol.
Apabila diletakkan dalam
konteks target yang hendak dicapai dari pemilu, kekalahan Foke-Nara
harus dibaca sebagai bentuk hukuman nyata pemilih bagi parpol yang tak
peduli dengan suara rakyat. Bahkan lebih jauh dari itu, hasil pemilihan
gubernur DKI benar-benar menjadi tamparan hebat di tengah hegemoni
parpol menuju Pemilu 2014.
Tetap sentralistik
Hadirnya
pasangan Jokowi- Basuki memang terbilang unik. Selain pendatang baru
di tengah belantara politik Jakarta, keduanya lebih tepat dikatakan
sebagai eksperimen PDI-P dan Gerindra di tengah ”kerumunan” parpol yang
sejak semula cenderung merapat ke Foke-Nara. Karena itu, tidak terlalu
berlebihan pendapat politikus senior Partai Golkar, Zainal Bintang,
hasil Pilkada DKI menunjukkan bulan madu politik pencitraan dan parpol
yang hanya berorientasi pada kekuasaan sudah di ujung senja (Kompas,
22/9).
Sebetulnya, tawaran untuk memilih tokoh alternatif tidak
hanya bersumber dari duet Jokowi-Basuki. Ketika putaran pertama, Faisal
Basri-Biem Benjamin juga hadir sebagai calon alternatif. Dengan adanya
calon alternatif yang tidak tunggal, keberhasilan pasangan
Jokowi-Basuki membuktikan bahwa calon alternatif masih perlu dukungan
mesin yang efektif untuk meraih dukungan pemilih. Tanpa itu, bukan
tidak mungkin nasib yang menimpa Faisal-Biem akan berlaku pula kepada
Jokowi-Basuki.
Terlepas dari keberhasilan pasangan racikan PDI-P
dan Gerindra ini, apabila boleh sedikit menoleh ke belakang, hadirnya
pasangan Jokowi-Basuki belum merupakan hasil dari sebuah proses
internal parpol yang terbuka dan partisipatif. Dengan posisi itu,
hadirnya duet Jokowi-Basuki tetap harus dipandang sebagai bentuk
hegemoni parpol dengan proses yang sentralistik (top- down). Untungnya
hasil pilihan hegemoni masih bisa diterima pemilih sebagai tokoh
alternatif.
Sekiranya Jokowi-Basuki ditawarkan sebagai hasil dari
sebuah proses yang terbuka dengan pola yang bottom-up, kehadirannya
akan kelihatan lebih elegan dan orisinal. Banyak kalangan berpikir,
dengan proses yang partisipatif, parpol dipaksa memiliki pola yang
demokratis dalam mengajukan calon guna mengisi jabatan politik
strategis, termasuk dalam pengisian jabatan kepala daerah. Tanpa sebuah
pola yang baku, hegemoni parpol sulit dipangkas. Dalam proses
pemilihan gubernur DKI, misalnya, parpol bisa menawarkan calon
alternatif yang diterima rakyat. Namun, karena pola internal yang tidak
baku dan tak terbuka, sangat mungkin di tempat lain terjadi perilaku
yang sebaliknya.
Menuju 2014
Merupakan
pilihan bijak sekiranya kita segera keluar dan meninggalkan euforia
kemenangan duet Jokowi-Basuki. Menuju Pemilu 2014, terutama pemilihan
presiden (dan wakil presiden), berharap kepada parpol untuk menghadirkan
tokoh alternatif sangat mungkin seperti seekor burung pungguk
merindukan bulan. Bagaimanapun, sejauh ini belum kelihatan partai
membuka dan menyediakan ruang bagi calon alternatif.
Kalau ada
yang berpandangan bahwa kemunculan Jokowi-Basuki membuka peluang
munculnya kader potensial dari internal parpol yang selama ini terhalang
hegemoni elite tertinggi parpol menuju Pemilu 2014, pandangan demikian
akan segera terkoreksi. Melihat gejala saat ini, parpol lebih banyak
memosisikan diri sebagai ”perahu” bagi elite tertinggi menuju 2014. Pola
yang mapan terbangun, posisi sebagai elite tertinggi parpol menjadi
semacam jalan bebas hambatan menuju posisi RI-1 atau RI-2.
Karena
itu, kader potensial yang berasal dari internal parpol yang berpeluang
jadi calon alternatif sulit muncul ke permukaan. Dalam hal ini, figur
seperti Teras Narang dan Ganjar Pranowo (PDI-P), Jusuf Kalla dan
Hajriyanto Tohari (Golkar), Yuddy Chrisnandi (Hanura), Lukman Hakim
Saifuddin (PPP), Fadli Zon (Gerindra), serta puluhan nama lainnya tak
mungkin menjadi figur alternatif. Mereka hanya mungkin hadir sekiranya
parpol melakukan proses perekrutan yang bottom-up dan terbuka.
Kalau
yang dari internal tidak mudah, tentunya calon alternatif dari luar
parpol jauh lebih sulit. Merujuk aturan yang ada, kesulitan ini
benar-benar jadi jalan buntu karena tak tersedianya ruang bagi calon
perseorangan (yang bukan diajukan parpol) menjadi calon presiden. Karena
itu, figur seperti Moh Mahfud MD, Anies Baswedan, Irman Gusman, Imam B
Prasodjo, Teten Masduki, dan sederetan nama lain sulit hadir menjadi
calon sebagai alternatif. Bahkan, kalau publik mendesak PDI-P dan
Gerindra mengajukan Jokowi kembali sebagai calon alternatif menuju
Pemilu 2014, kedua parpol ini pasti akan menolak.
Dalam
batas-batas tertentu, hasil pemilihan gubernur DKI Jakarta memberi
sedikit ”kemewahan” dalam panggung politik negeri ini. Namun, kemewahan
akan munculnya calon alternatif dalam Pemilu 2014 hampir mustahil
terjadi. Kemustahilan itu hanya mungkin meluruh kalau parpol mau dan
mampu mengambil pelajaran dari tamparan yang hadir dari hasil pemilihan
gubernur DKI.
Saldi Isra
Guru Besar Hukum Tata Negara dan
Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas,
Padang; Anggota Badan Pekerja Forum Kebangsaan Gerakan Indonesia Memilih
Editor :
Inggried Dwi Wedhaswary